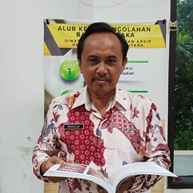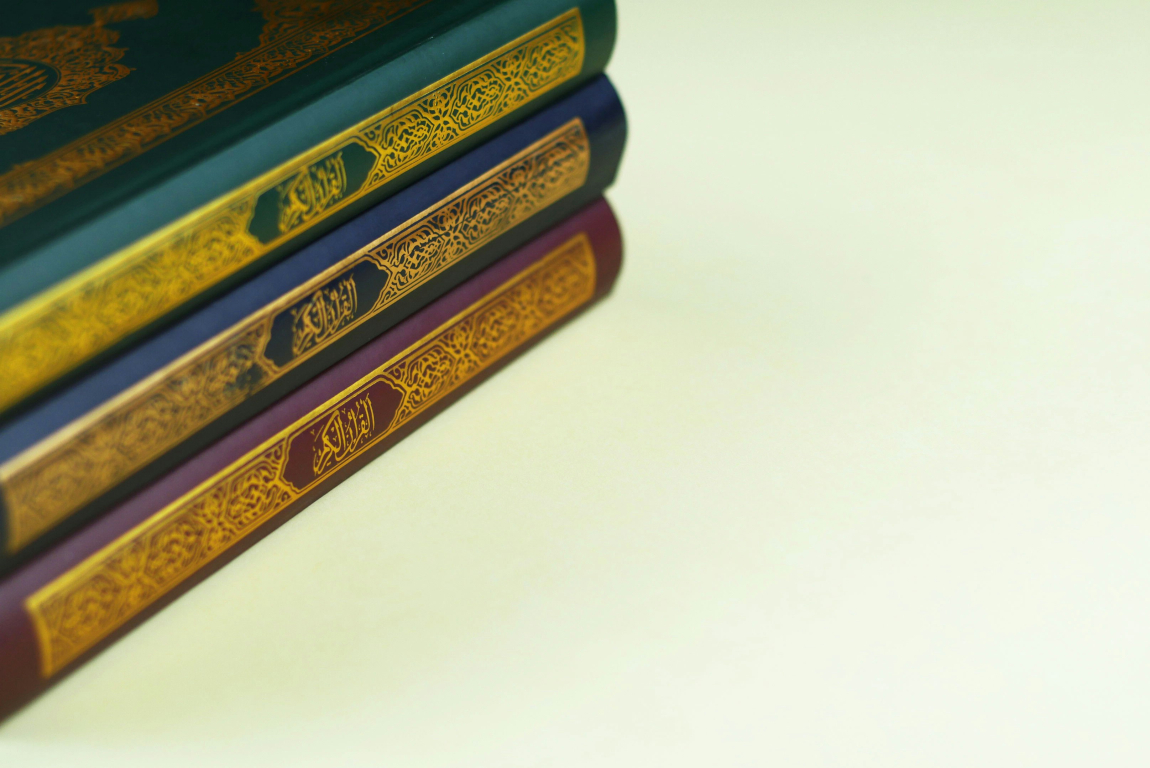Sumber Foto : Freepik
SEJARAH LITERASI DI INDONESIA
Mereka yang tidak mengingat masa lalu dikutuk untuk mengulanginya
- Pendahuluan
Dalam kajian arkeologis, filologis, dan antropologis sesungguhnya literasi masyarakat Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang, bahkan telah ada sebelum istilah literasi diluncurkan oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) atau Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan kebudayaan Persarikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1946 mengenai global literacy effort. Oleh karena itu menurut para arkeolog, filolog, dan antropolog bahwa literasi tulis-menulis di nusantara sudah berkembang mulai abad ke-5 sejak kehadiran Hindu dan Budha hingga memasuki abad ke-13 ketika agama Islam datang.
Pada masa Hindu dan Budha sudah dikenal bahasa Sansekerta dan aksara Pallawa, dan pada era Islam berkembang bahasa Arab dengan aksara Arab-Jawa dan Arab-Melayu. Berdasarkan penuturan beberapa orang arkeolog, literasi (dalam artian literasi gambar) telah ada pada masa pra-sejarah ribuan tahun yang lampau. Selain itu, seorang Indonesianis dari Universitas Hamburrg, Jan van der Putten juga turut memaparkan tentang tradisi menulis. Menurut Jan van der Putten, Indonesia memiliki tradisi lisan yang kaya, namun tradisi menulis pun sudah muncul sejak berabad-abad silam. Menurutnya, kekayaan tradisi lisan dan tradisi menulis yang dimiliki, dipelihara dan digunakan oleh kalangan tertentu atau untuk tujuan khusus. Salah satunya digunakan untuk penyebaran agama (religion spread)..
Putten mengungkapkan bahwa deferensiasi kekhasan tradisi menulis pada setiap tempat di Indonesia berbeda-beda. Sebagai contoh, manuskrip di Jawa, yang ditulis perpaduan antara tulisan dan gambar di daun lontar dan daun palem yang dilkukan oleh kalangan terbatas seperti anggota kerjaan di Jawa. Sedangkan di Sumatera Selatan banyak ditemukan berupa puisi dan surat cinta. Hal ini disebabkan oleh hubungan pria dan wanita di Sumatera Selatan pada masa dahulu sangat diatur ketat. Dengan demikian, jika ditinjau dari perspektif ini maka masyarakat nusantara dan bangsa Indonesia sesunguhnya secara empiris telah tumbuh dan berkembang literasinya.
Pada fase-fase awal, literasi diartikan sebagai melek aksara atau tidak buta huruf. Sehingga literasi secara umum selalu diidentikan dengan kemampuan membaca. Padahal yang dimaksudkan literasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Sementara literasi ditambah kemapuan menghitung sering kali diistilahkan sebagai literas dasar (basic literacy).
Seiring perkembangan dan perubahan di tengah masyarakat serta pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terlebih lagi pada era digital saat ini, konsep dan definisi serta pemaknaan literasi semakin kompleks dan variatif. Beberapa lembaga yang memperkenalkan konsep literasi, di antaranya World Ekonomic Forum (WEF) dan UNESCO melalui literasi untuk kesejahteraan (functional literacy tahun 1965).
Akan tetapi, sangat disayangkan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat tersebut tidak dapat diikuti oleh bangsa Indonesia dalam sejarah peradabannya. Ada faktor historis, mengapa bangsa Indonesia tertinggal jauh bila dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Ada asumsi sejarah bahwa bangsa Indonesia terlalu lama dijajah oleh bangsa asing, akibatnya dininabobokan oleh pengaruh penjahan Portugis (1509-1595), Spanyol ( 1521-1529), Belanda (1602-1942), Prancis (1806-1811), Inggris (1811-1816), dan Jepang (1942-1945), sehingga bangsa Indonesia terbuai dan terlena, serta tidak berdaya dan jalan ditempat.
Dalam dunia pendidikan, fakta menunjukkan bahwa berdasarkan hasil berbagai survei yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa literasi merupakan masalah yang sesius dalam dunia pendidikan di Indonesia. Data dari Word’s Most Literacy Nations, yang dilakukan oleh Central Connecticut State Univesity pada tahun 2016, mengindikasikan bahwa Indonesia menempati urutan ke-60 dari 61 negara partisipan survei dalam kemampuan literasi. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS), yaitu sebuah studi internasional dalam bidang membaca pada anak-anak di seluruh dunia, yang disponsori oleh The International Assosiasion for the Evalutions Achievment. Hasilnya menemukan bahwa rata-rata anak Indonesia berada pada urutan keempat dari bawah, dari 45 negara di dunia. Data yang dirilis oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tahun 2017, frekuensi membaca orang Indonesia rata-rata hanya tiga sampai empat kali per minggu.
Rendahnya tingkat literasi di Indonesia, tentunya menjadi sorotan serius bagi pemerintah, pemerhati, dan peneliti. Dengan fenomema ini munculah keadaan darurat dalam peningkatan mutu pendidikan di Indoseia. Untuk mengatasi hal semacam ini, sebenarnya banyak program pemerintah yang mempromosikan kegiatan literasi. Misal, dikeluarkannya Kepmendikbud Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pendidikan Akhlak, di dalamnya tersurat adanya program Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yang harus diterapkan selama 15 menit sebelum pelajaran sekolah dimulai di kelas. Dalam kurikulum dan proram pengajaran telah diupayakan untuk mengembangkan kemampuan literasi siswa. Di kelas, di sudut sekolah siswa diarahkan untuk membaca, siswa sudah dikenalkan dengan dunia literasi.
Dalam persfektif sejarah Islam, idiom yang dikenalkan oleh Allah SWT kepada Rasulnya, Nabi Muhammad Saw adalah tentang literasi. Di dalam Al-Quran Surat Al-“Alaq, surat ke 90 ayat 1-5 adalah tentang perintah membaca sampai diulang dua kali, menunjukkan pentingnya literasi. Perintah itu tersurat pada ayat 1 dan 3, kemudian pada ayat keempat tersirat tentang perintah menulis. Untuk dapat membaca, metodenya harus melalui proses belajar. Dalam konteks turunnya Surat Al-‘Alaq ini mengiisyaratkan bhwa perintah pertama yang paling fundamental dalam sejarah peradaban sejarah umat Islam adalah perintah membaca Al-Quran, identik dengan perintah menyebut nama Allah, yang menciptakan dan mengajarkan manusia dengan qalam. Jadi, klausulnya perintah membaca sederet dengan perintah menulis. Sistematikanya perintah membaca lewih awal kemudian dibarengi dengan perintah menulis.
Dalam kajian metodelogis, proses menelaah, mengkaji, dan menganalisis realitas sosial inilah yang kemudian disebut budaya literasi. Namun demikian, sebaiknya kajian tentang literasi dipelajari bukan sebagai fenomena otonom yang dapat dipahami dalam abstraksi konteksnya, atau melalui kelembagaan yang ketat. Melainkan, literasi adalah bagian dinamika sosial yang kompleks, yang terkait dengan konteks sejarah tertentu. Pendekatan ini, bila dilakukan, memiliki keuntungan karena tidak terfokus pada pendidikan yang dilembagakan, tetapi cenderung mencakup saluran yang lebih informal untuk proses pembelajaran. Untuk mengaktualisasikan hal ini, di Indonesia telah merumuskan berbagai macam kebijakan dalam bidang pendidikan.
B. Konsep dan Kerangka Dasar Literasi
Di awal telah disinggung tentang definsi literasi, oleh karenanya, dalam dunia nyata berkomunikasi baik melalui media lisan maupun aural hidup berdampingan dan saling berinteraksi, tidak hanya dalam budaya yang sama, tetapi juga dalam individu yang sama. Dengan kata lain, literasi dapat dipahami sebagai kemampuan menggunakan informasi cetak dan tertulis untuk dapat berfungsi di masyarakat, untuk mencapai tujuan seseorang, dan untuk mengembangkan pengetahuan dan profesi seseorang.
Menurut Kirsch, meningkatnya penerimaan akan pentingnya pembelajaran seumur hidup telah memperluas pandangan dan tuntutan membaca dan keaksaraan. Keaksraan tidak lagi dilihat sebagai kemampuan yang dikembangkan selama bertahun-tahun awal sekolah, tetapi dipandang sebagai seperangkat ketrampilan, pengetahuan, dan strategi yang terus berkembang yang dibangun individu, sepanjang hidup mereka dalam berbagai konteks dan melalui interaksi sosial dengan teman sebaya dan dengan komunitas yang lebih besar tempat mereka berpartisipasi. Para sejahrawan telah mengingatkan bahwa jenis dan tingkat ketrampilan literasi yang diperlukan untuk berpartisipasi di bidang ekonomi, kewarganegaraan, pengasuhan anak, dan kemajuan individu pada era tahu 1800 sangat berbeda dari yang dibutuhkan pada era tahun 1900 dan dari yang diperlukan pada era tahun 2000 begitu seterusnya. Saat ini, dunia berkembang dengan teknologi yang super maju, di mana jumlah dan jenis bahan tertulis bertambah begitu pesat dan semakin banyak warga diharapkan untuk menggunakan informasi dengan cara baru dan lebih kompleks.
Selain literasi membaca, dalam kehidupan sehari-hari dan dalam konteks pendidikan literasi, literasi numerasi dan sains adalah aspek pendidikan yang penting untuk memahami lingkungan, kesehatan, ekonomi, dan masalah-masalah lainnya yang dihadapi oleh masyarakat modern, yang hidup di alam ilmu pengetahuan dan teknologi. Hampir sudah dapat dipastikan kemampuan literasi numerasi dan sains oleh para siswa akan memberikan implikasi positif bagi kemajuan bangsa dan negara dalam pengembangan teknologi dan untuk meningkatkan daya saing internasional di kancah persaingan global. Oleh karenanya, kemampuan dalam berhitung saja jelas tidak cukup lagi.
C. Tradisi Membaca Dalam Islam
Sejarah telah mencatat tentang diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad Saw ketika sedang berkholawat di Gua Hiro’ pada malam Senin, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan (6 Agustus 610 Miladiyah), tahun ke-41 kelahiran Nabi. Perintah pertama yang disampaikan adalah iqra’ membaca, perintah ini diulang sampai dua kali, sebagaimana tercantum pada ayat pertama dan ketiga Surat Al-‘Alaq, surat ke-96.. Kemudian pada ayat yang keempat disebutkan, al-ladzi al-lama bil qalam, yang mengajarkan dengan qalam, pena (tulisan). Jelas sekali kalau perintah membaca disebutkan dalam bentuk fi’il amar (kalimat perintah). Sedang mengenai perintah menulis disebutkan dalam bentuk fi’il madhi (kata kerja). Kemudian perintah menulis juga disebutkan dalam Al-Quran pada Surat Al-Qalam, surat ke-68 ayat 1, disebut sampai dua kali, “nun, wa al-qalam wama yasthurun”, Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Dan jangan lupa, para mufasir sendiri memaknai Al-Quran kitab bacaan.
Dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia telah memunculkan empat teori: pertama, teori Gujarat, yang menyebutkan bahwa Agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim (Gujarat) yang berdagang di nusantara pada abad ke-13. Teori Gujarat ini didukung dengan ditemukannya nisan makam Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1927. Pencetusnya Pijnappel dari Universitas Leiden dan Snouk Hurgronje. Kedua, teori Makkah, yang dicetuskan oleh Buya Hamka berpendapat bahwa Agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan pembawanya berasal dari Arab (Mesir). Teori ini didukung dengan adanya berita Cina Dinasti Tang yang menuturkan ditemukannya daerah hunian wirausahawan Arab Islam di pantai barat Sumatera Utara. Ketiga, teori Persia berpendapat bahwa Agama Islam masuk ke Indonesia dari Persia singgah di Gujarat pada abad ke-3. Hal ini dibuktikan bahwa kebudayaan Indonesia memiliki kesamaan dengan kebudayaan Persia. Pencetusnya adalah Prof. Hoesein Djajadiningrat. Dan, keempat teori Tiongkok, berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh perantau dari Tiongkok. Dalil yang dikemukakan adalah fakta bahwa orang Tiongkok sudah ada di kepulauan nusantara sejak abad pertama hijriyah. Pencetusnya adalah Kong Yuanzhi, yang didukung juga oleh Buya Hamka.
Lalu bagaimana masuknya Agama Islam ke Indonesia kaitannya dengan tradisi literasi ? Sejarah menjelaskan bahwa Indonesia memiliki hutang budi yang besar terhadap peradaban Islam dalam soal pengenalan tradisi baca-tulis pada masa lalu. Dengan masuknya Agama Islam ke kepulauan nusantara pada masa itu masyarakat Indonesia sudah diajarkan baca-tulis dengan belajar huruf Arab. Aksara Arab sendiri masuk ke kepulauan nusantara bersamaan dengan masuk Islam ke Indonesia pada abad ke-14 masehi. Huruf atau aksara Arab pada masa itu dikenal dengan huruf Arab gundul, yaitu huruf yang didasarkan pada huruf hijaiyah, yang digunakan untuk menulisan ucapan bahasa Melayu. Dalam penggunaannya beberapa huruf hijaiyah tersebut telah dimodifikasi atau ditambah dengan beberapa huruf untuk mengakomodasi bunyi ujaran yang tidak ada dalam huruf hijaiyah. Hasilnya huruf-huruf hijaiyah yang telah dimodifikasi inilah yang digunakan di masyarakat, dalam bentuk huruf Arab gundul.
Disebutkan pada saat kerajaan-kerajaan Islam pertama kali berdiri di Semanjung Melayu, huruf Arab Gundul (pegon) diterapkan sebagai abjad resmi kerajaan. Kerajaan tersebut, antara lain Samudra Pasai, Kesultanan Malaka, dan Kesultanan Johor. Ketiga kerajaan tersebut merupakan pelopor dalam penggunaan huruf Arab gundul untuk menulis bahasa Melayu. Adapun untuk masyarakat di Pulau Jawa dan Madura, bentuk huruf Arab gundul agak berbeda karena adanya modifikasi huruf-huruf tambahan untuk bunyi yang tidak dapat dikembangkan dengan huruf Arab gundul. Huruf ini dikenal dengan sebutan abjad pegon. Namun dalam perkembangan selanjutnya semua abjad Arab tersebut disebut Arab gundul termasuk abjad pegon yang digunakan di Pulau Jawa dan Madura.
D. Kebijakan Literasi di Indonesia : Rekontekstualisasi Sejarah
Bung Karno, seperti yang sering kita dengar:selalu mendengungkan jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Berpijak pada kalimat tersebut, maka sejarah terkait literasi di Indonesia harus menjadi refleksi untuk kemudian dikontekstualisasikan dalam bentuk kebijakan. Terlebih mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, seharusnya memiliki tradisi yang kuat dalam hal literasi. Karena Al-Quran sendiri sebagai kitab bacaan, ayat pertama yang diturunkan tentang iqro’, perintah membaca diulang sampai dua kali, kemudian dilanjutkan dengan perintah menulis. Maka, tidak dapat dipungkiri bahwa budaya literasi adalah kunci utama untuk kemajuan pendidikan di Indonesia.
Kemampuan membaca, melihat, mendengar, menulis, dan berbicara adalah syarat utama untuk membangun tradisi akademisi di Republik ini. Konsekuensinya, pemerintah harus berupaya sekuat tenaga menjadi motor penggerak untuk meningkatkan kemampuan literasi yang merupakan kunci dari ilmu pengetahuan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah harus berkolaborasi yang sinegis dengan semua pemangku kepentingan, terutama sekali dengan institusi pendidikan, warga sekolah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat pemerhati dan penggiat literasi.
Untuk menumbuhkembangkan budaya literasi tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Dengan adanya peraturan ini merupakan upaya untuk menumbuhkan budi pekerti anak di mana sekarang ini pada era globalisasi literasi sudah dianggap sebagai kebutuhan primer. Oleh karena itu, menuntut adanya peranan pemerintah untuk menyediakan dan memfasilitasi system dan pelayanan pendidikan sesuai ketentuan pasal 31 ayat 3 yang menyatakan, “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam kerangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”. Ayat ini membahas dan menjelaskan tentang program literasi.
Berdasarkan landasan tersebut, pemerintah telah mengambil satu langkah konkret untuk meningkatkan kemampuan literasi genersai muda Indonesia dengan mengembangkan sekolah sebagai organisasi pembelajaran dengan suatu gerakan yang dinamakan Gerakan Literasi Nasional (GLN). Tujuan utama GLN ini adalah untuk membangun budaya litersai pada ranah pendidikan, yaitu keluarag, sekolah, dan masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya dibentuk suatu gerakan yang disebut
GLS (Gerakan Liteasi Sekolah), yang melibatkan semua warga sekolah, yaitu guru, peserta didik, orang tua murid/wali murid dan masyarakat sebagai bagian dari ekosistem pendidikan. Dalam salah satu program kerjanya, GLS ini mengharuskan adanya pembelajaran membaca buku selama 15 menit sebelum jam peljaran di kelas dimulai. Kebijakan ini tentu sejalan dengan pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
Kaitannya dengan revisi terbaru tahun 2017 dijelaskan bahwa salah satu agenda atau fokus utama dalam implementasi K-13 adalah penguatan literasi. Pengembangan literasi secara eksplisit diwujudkan dalam Kompetensi Dasar dalam KI-3 dan KI-4 dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kemudian dituangkan dalam kegiatan pengembangan literasi dalam KD Mapel Bahasa Indonesia dengan tujuan adanya aktivitas yang dilakukan oleh guru dan peserta didik yang mengarah pada pengembangan literasi.
E. Penutup
Dari penjelasan di atas, ternyata bahwa perkembangan literasi di Indonesia mempunyai sejarah yang cukup panjang. Akan tetapi, sejarah yang cukup panjang itu tidak mengajarkan kepada kita untuk lebih maju, lebih unggul dan lebih mandiri dalam penerapan budaya literasi, malahan sebaliknya budaya literasi bangsa Indonesia makin tetinggal jauh dari bangsa-bangsa lain di dunia. Di kawasan regional negara-negara ASEAN pun, Indonesia tertinggal, dari Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam, kita hanya setingga lebih maju dari Kamboja.
Dari tulisan artikel ini, pelajaran apa yang dapat kita petik. Ada kata bijak yang diungkapkan oleh George Santayana, “ Mereka yang tidak mengingat masa lalu dikutuk untuk mengulanginya”. Barang kali pesan yang disampaikan oleh Santayana itu, kesalahan sejarah masa lalu, jangan diulang pada masa sekarang dan masa mendatang. Sejarah masa lalu, pelajaran sangat berharga untuk menatap masa yang lebih baik. Jean Chretien mengatakan, “Anda harus melihat sejarah sebagai evolusi masyarakat”. Begitu juga yang pernah dikatakan oleh Arnold J. Toynbee, “ Sejarah adalah visi dari ciptaan Tuhan yang bergerak”. Artinya bahwa dengan melihat masa lalu kita menata masa depan yang lebih baik. Budaya literasi masa lalu harus diperbaiki dan ditingkatkan pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Jika selama ini kita termasuk orang yang tidak perduli dengan gerakan literasi, pada masa sekarang dan masa yang akan datang kita adalah orang yang giat menggerakan budaya liiterasi di tengah-tengah masyarakat kita.